
Sabtu, 3 Januari 2004.
Rangga mengempaskan tubuhnya yang lelah di atas kasur tipis di kamarnya yang sempit. Matanya seolah digantungi berkilo-kilo pemberat. Lima menit tadi dia mengurungkan niatnya untuk mengudap isi lemari makan setelah menguap berkali-kali. Tumis udang dan sayur rebung kesukaannya dia biarkan utuh di dalam lemari. Nanti saja, pikirnya.
Semilir angin yang menerobos kisi-kisi jendela kamar membuat kantuk kian terasa. Perlahan mata Rangga memejam, mimpi hampir datang kalau saja bunyi monofonik dari ponselnya terdengar. Rangga ingin mengabaikan pesan yang masuk tapi rasanya enggan tidur dengan rasa penasaran. Setengah terpejam dibacanya sms itu.
Ga, berenang yok!
Hm, apaan sih Fajar ngajakin berenang jam segini? Kan tahu sendiri semalam barengan begadang di kantor, gumam Rangga. Diketiknya sebaris kalimat balasan.
Maaf, Jar, aku mau tidur. Ngantuk berat.
Terkirim.
Sembarangan Rangga meletakkan ponsel candy bar keluaran terbaru dan bergegas memeluk guling lebih erat. Tapi lagi-lagi dia terbangun. Kali ini karena sebuah panggilan dari luar kamar.
“Gaaa, bantuin Ayah! Bunda mau belanja.” Itu suara Bunda dari dapur yang terletak bersebelahan dengan kamar Rangga. Ugh!
“Yaa, Bun,” Rangga beranjak malas dari ranjang. Dikuceknya mata berkali-kali.
“Ayah sedang nyemen dinding rumah kakek, tuh. Bantuin aduk semennya,” titah Bunda. Rangga mengangguk tak membantah.
Dengan langkah pelan, pemuda dua puluh dua tahun itu menuju rumah kakeknya yang berjarak belasan meter dari rumahnya. Dia melihat lelaki gagah itu sedang mengayak pasir sendirian. Dua tangannya memegang pegangan ayakan dan mengayunkannya maju mundur. Pegangan lain dia ikatkan dengan tali ke batang kelapa.
“Sini Rangga bantuin, Yah,” kata Rangga. Ayahnya tersenyum. “Sana ambilkan air. Lalu aduk pasir yang halus dengan semen dan tuang air. Sekopnya di sebelah sana,” tangan kokoh berbulu halus itu menunjuk. Rangga menurut.
Selama setengah jam berikutnya Rangga berkutat dengan pekerjaan mengaduk adonan semen. Setelah adukan tercampur sempurna, dia memindahkan sebagian adonan ke sebuah ember plastik dan membawanya menuju sebuah dinding yang sedang diplester.
Dengan sendok semen, lelaki empat puluhan itu cekatan menempelkan adonan semen dan meratakannya. Begitu berulang-ulang.
“Semalam begadang, ya?” tanya ayah Rangga ketika melihat anaknya sesekali menguap dan matanya merah. Rangga mengangguk.
“Ya sudah, bikin satu adukan lagi, lalu tidur. Biar Ayah yang lanjutkan,” kata lelaki itu tanpa menghentikan gerakan tangannya yang terlatih. Rangga kembali mengangguk.
Setelah mencuci tangan dan kaki serta berganti baju, Rangga kembali ke kamarnya dan berbaring. Sejenak kemudian kantuk menyergapnya. Entah berapa lama dia tertidur tanpa mimpi, sampai sebuah panggilan yang lebih tepat disebut jeritan membangunkannya.
“Rangga! Ayah jatuh!”
Rangga tersentak dari tidur. Ayah jatuh?
Rangga bergegas keluar dari kamar dan menuju asal suara : dapur. Di situ dia lihat ayahnya terduduk di lantai dengan sebelah tangan berpegangan pada tepi meja makan. Matanya memejam dan dahinya berkerut seakan menahan sakit. Di sebelahnya ada Bunda, dan adiknya Tante Lila, sedang memegangi masing-masing sebelah tangan ayahnya.
“Rangga! Bantuin angkat Ayah!” seru Bunda dengan suara gemetar. Ada apa dengan suamiku? bisik gelisah hatinya.
Kantuk Rangga lenyap. Bergegas dia papah lelaki tinggi besar yang sepertinya tengah keletihan sehingga sulit untuk berjalan sendiri. Dengan susah payah mereka membawa tubuh besar itu ke kamar depan.
“Tiduran dulu, Yah,” kata Rangga setelah Ayahnya berhasil dibaringkan. Lelaki itu tak menjawab. Matanya terpejam dan dadanya turun naik. Rangga melirik jam di dinding : 11.25.
“Ayah kenapa, Ga?” tanya Bunda lebih kepada dirinya sendiri. Rangga menggeleng. Dengan tatapan cemas Rangga memperhatikan Bundanya mengompres dahi Ayah. Mata lelaki itu masih terpejam, tapi dadanya kini lebih tenang.
“Mungkin Ayah kecapekan dan kepanasan,” simpul Bunda. Ah, semoga memang cuma karena itu, harap hati Rangga.
“Kau tidur saja lagi. Biar Bunda jaga Ayah.”
Rangga beranjak kembali ke kamarnya. Tante Lila juga keluar dari kamar dan menuju rumahnya yang terletak di belakang rumah Rangga.
Waktu berjalan seolah sangat lambat. Masih dengan diliputi sedikit kecemasan, Rangga mencoba tidur. Hanya beberapa menit rasanya sampai dia mendengar lagi jeritan dari kamar sebelah. Tanpa menunggu dipanggil dia bergegas datang.
“Ga, Ayah, …” suara Bunda hilang seolah tercekik kecemasan. Dia terduduk sambil menatap tubuh suaminya dengan pandangan nanar. Rangga melihat tubuh Ayahnya kini ada di lantai. Susah payah Rangga mengangkat tubuh Ayahnya kembali ke ranjang. Selain mata yang terpejam, napas Ayah kini terdengar semakin sesak.
Di luar kamar, banyak orang telah berkumpul; dua adik lelaki Rangga yang masih berseragam sekolah, beberapa saudara yang tinggal berdekatan, juga tetangga dekat sebelah rumah. Mata mereka semua bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi?
“Ga, coba panggil Wak Syafri. Minta datang ke mari. Bilangin, Ayah sakit mendadak,” usul Tante Lila. “Sudah, nggak usah ganti celana lagi. Langsung aja!” tegurnya ketika Rangga ingin mengganti celana pendek dan kaus singletnya. Rangga menurut.
Rangga berlari kencang menuju rumah abang Ayahnya yang berjarak seratus meter dari rumah. Lelaki yang dia panggil Uwak itu punya kemampuan lebih untuk menyembuhkan orang dengan air yang sudah dirajah dengan doa. Semoga uwak ada di rumahnya, mohon Rangga dalam hati.
Di depan pintu rumah sederhana, dengan napas terengah Rangga mengucap salam.
“Waalaikumsalam,” sahut seorang lelaki. Ah, syukurlah! Itu Wak Syafri.
“Wak, Ayah, Wak!” nada panik keluar dari mulut Rangga. “Ayah tiba-tiba jatuh dan sampai sekarang belum sadar! Uwak bisa ‘kan datang ke rumah?”
Wak Syafri menghela napas. Bukannya dia tak mau datang, tapi rematik yang belakangan kerap datang membuatnya tak sanggup berjalan jauh. Wak Syafri mengembuskan napas.
“Pulanglah duluan, Uwak menyusul,” perintahnya. Rangga segera berlari pulang mendengar jawaban uwaknya.
Sepuluh menit kemudian lelaki paruh baya itu datang membonceng sepeda motor tetangga. Segera dia memberi perintah, “Ambilkan air putih segelas.”
Wak Syafri membacakan sederetan doa sambil memegang gelas air itu dekat bibirnya. Semua mata memandang penuh perhatian pada lelaki itu. Selesai membaca doa, Wak Syafri menyerahkan gelas itu pada Bunda. “Minumkan ke Adam. Pakai sendok.”
Sesendok demi sesendok cairan bening itu memasuki tenggorokan Ayah diiringi tatapan cemas Bunda. Perlahan meski matanya masih terpejam tapi napas Ayah perlahan kembali normal. Raut wajah Bunda kembali disaput harapan. Wak Syafri masih menunggu di ruang depan.
“Sepertinya Ayahmu sudah baikan. Wawak pulang dulu ya,” pamitnya pada Rangga. “Diana, aku pulang dulu ya.”
Bunda keluar dari kamar. “Makasih banyak, Bang.”
Menit demi menit berlalu seperti siput. Bunda duduk di samping ranjang sambil sesekali membelai rambut suaminya dengan penuh kasih. Sesekali disekanya air mata yang terbit di ujung ke dua mata lelaki yang telah menemaninya selama puluhan tahun. Dia tak mengerti, kenapa suaminya menangis.
“Ga, lihat Ayah,” tunjuk Bunda. “Ayah menangis.”
Rangga mendekati wajah Ayahnya. Ya, ada butiran bening yang timbul di dua sudut mata. Apakah Ayah merasa sedih? Apa yang dia sedihkan? Apakah dia sedang bermimpi? Tanya tanpa jawab berkecamuk di benak Rangga. Tak kunjung bertemu penjelasan, Rangga memilih duduk di kursi ruang tamu. Melamun. Dua adiknya sedang makan di dapur.
“Abaaaaang!”
Ya Allah! Kenapa Bunda menjerit lagi? Di dalam kamar, Rangga melihat Bundanya sedang memeluk tubuh Ayahnya yang terguling lagi dari tempat tidur. Dada lelaki itu naik turun dengan cepat. Matanya tetap terpejam.
“Ayah kenapa, Bun?” tanya Rangga panik. Dia berlutut di sebelah Bunda, membantu mengangkat tubuh Ayah.
“Ayah tadi kesakitan. Dia bergerak-gerak terus di tempat tidur, akhirnya jatuh. Bunda nggak sanggup menahan badannya,” Bunda berusaha menjelaskan tanpa mengalihkan pandangan dari suaminya yang telah kembali dibaringkan di ranjang.
“Bang, abang kenapa? Bangun, Bang! Bangun!” Bunda memohon sambil membelai rambut Ayah. Tak ada reaksi apapun. Hanya dada Ayah yang naik turun dengan perlahan. Rangga merasa hatinya patah.
“Ga, panggil Wak Syafri! Panggil sekarang!” Di antara isak yang kemudian menghebat menjadi tangisan, Bunda memberi perintah. Rangga berlari secepat dia bisa. Dadanya risau luar biasa. Ini kejadian yang pertama dialami ayahnya. Mereka tak tahu harus bertindak apa.
Tanpa mengucap salam, Rangga menerobos rumah uwaknya dan terus menuju bagian belakang. Di samping dapur dia temui Wak Syafri tengah duduk sendiri sambil membaca sebuah kitab.
“Wak! Ayah jatuh lagi! Wawak tolong datang, ya Wak. Tolong ya,” ada nada putus asa dalam permohonan Rangga. Tanpa menunggu jawaban dia bergegas kembali ke rumah.
Dari kejauhan Rangga melihat sebuah mobil terparkir di depan rumahnya. Dia tak sempat berpikir, kakinya dia paksa terus berlari. Ketika sampai di dekat mobil itu, baru dia sadari itu milik tetangga sebelah. Ahyar, anak lelaki tetangga sebelah telah bersiap di kursi pengemudi. Dan ketika dia menoleh ke arah rumah, dilihatnya tubuh besar Ayah tengah dibopong oleh beberapa orang. Bunda mengikuti dengan mata sembab dan wajah kalut. Adik-adiknya tengah menangis.
“Ga, masuk duluan ke dalam. Pegang kepala Ayahmu,” Dani, saudara lelaki Bunda memberi perintah.
“Ya, Om,” Rangga segera masuk dan bersiap menyambut tubuh Ayahnya. Tubuh lelaki itu hangat. Matanya terpejam. Rangga mendaras doa di dalam hatinya. Bundanya ikut masuk dan memegangi kaki suaminya.
“Yar, berangkat!” Dani menepuk pundak Ahyar yang sigap menekan pedal gas dan mengemudikan mobil menuju Rumah Sakit Umum yang berjarak satu kilometer dari rumah. Berkali-kali Rangga mengusap wajah Ayahnya sambil membaca doa apa saja yang terlintas di kepala. Ya Allah, Ya Allah! Sembuhkan ya Allah! Di usapnya kening Ayah. Hangat masih terasa.
Mobil berhenti tepat di depan Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dua perawat lelaki bergegas menghampiri dengan membawa brankar. Dengan bantuan mereka, tubuh besar Ayah dipindahkan dan didorong menuju ruangan. Seorang dokter muda berjilbab biru sigap memeriksa. Raut wajah serius terpasang. Bunda berdiri dengan penuh kecemasan. Di luar ruangan, Rangga dan Om Dhani menunggu dengan tak kalah cemas.
Dokter muda itu mendesah panjang. “Ada bawa kain panjang, Bu?” tanya dia pada Bunda. “Ka..ka..in dokter?” Bunda beranjak keluar dan menyuruh Rangga mengambil kain batik panjang yang sempat dibawa.
“Ada di dalam tas biru. Badan Ayah mau diselimuti biar nggak dingin,” kata dia. Rangga segera melakukan yang diperintahkan bundanya.
“Ini, dok,” Bunda menyerahkan kain batik panjang. “Biar saya bantu selimuti,” imbuhnya. Dengan cekatan Bunda menghamparkan kain batik itu dari ujung kaki hingga menutupi leher suaminya.
“Sudah, dok?” tanya dia. Sebersit harapan muncul.
Dokter muda itu tak menjawab. Tangannya bergerak ke arah kain batik, mengait ujungnya dengan telunjuk dan ibu jari, menariknya hingga menutupi kepala.
Bunda nanar. “Dokter! Kenapa ditutupi sampai kepala? Kenapaaa?”
“Maaf, Bu. Bapak sudah pergi. Saya perkirakan sebelum sampai ke sini Bapak sudah meninggal. Saya ikut berduka,” kata dokter itu dengan wajah prihatin.
Tangis Bunda pecah. Isaknya begitu pilu mengiba. “Abang cuma jatuh! Kenapa bisa meninggal! Kenapaa?”
Raungan Bunda menyentakkan Rangga, Dani dan beberapa kerabat yang tiba belakangan. Semua harapan terasa berkeping. Kenyataan telah menghantam begitu keras. Kesedihan yang begitu nyeri.
Bunda terus menangis. Rangga susah payah menahan air mata yang terasa mendesak pelupuk. “Bunda, Bunda. Ikhlas, Bunda. Ayah sudah meninggal.” Rangga memeluk Bunda yang hancur perasaannya.
Rangga tahu, ucapannya itu percuma. Seperti setetes air yang jatuh di atas bara duka yang menyala. Tak memiliki arti. Dia merasa sedang menipu diri sendiri. Siapa mengira takdir hidup berbelok begitu tajam. Dua jam yang lalu ayahnya masih sehat-sehat saja, sedang mengaduk semen untuk menempel dinding rumah kakek. Masih ada senyum di wajahnya, nada kebapakan yang menenangkan. Masih ada tawa kecilnya. Masih ada…. masih ada.
Rangga memukul-mukul dadanya. Sakit di kulit dan daging masih tak setimpal dengan perasaan sakit di dalam hati. Rasa sakit yang timbul masih tak bisa mengalahkan sesak di dada yang seolah dihantam godam. Seorang kakak sepupu memeluknya dengan air mata bersimbah.
“Ikhlaskan ayahmu, Ga. Ikhlaskan dia.”
“Ikhlas gimana?” bentaknya. “Ayah meninggal! Padahal tadi pagi masih sehat. Masih kerja. Kenapa sekarang meninggal?!” Ternyata Rangga hanya bisa menenangkan orang lain, tapi tak bisa membujuk dirinya sendiri untuk ikhlas.
“Istighfar, Ga. Ini kehendak Allah. Istighfar!” perempuan itu berkeras memeluk Rangga dengan pipi yang sudah basah.
Astaghfirullah! Rangga mengucap kalimat itu berulang-ulang. Ya Allah, sungguh berat ujianmu. Rangga menoleh ke ruang UGD tempat jasad ayahnya terbaring. Di samping tubuh yang mulai mendingin itu Bundanya duduk terisak sambil menatap pilu suaminya. Tante Lila yang juga menangis memeluknya, seolah ingin memberi kekuatan. Rangga melangkah mendekat. Air mata di hapusnya dari pipi.
“Dokter, Ayah sakit apa?” tanya Rangga dengan suara yang sudah lebih tenang. Dokter muda berjilbab biru yang masih ada di ruangan tersenyum simpati.
“Lihat, dek,” tunjuknya pada telapak kaki Ayah,” warnanya kebiruan, kan?” sambungnya. Rangga mengangguk walau tak mengerti artinya.
“Kemungkinan Ayah kamu menderita penyakit jantung. Apa dia pernah periksa?”
Rangga menggeleng lalu menoleh pada Bundanya. Sambil menahan isak Bunda menjawab, “Abang nggak pernah mengeluh sakit. Dia memang begitu, nggak mau bikin keluarganya khawatir. Dia…dia…” tangis Bunda kembali pecah. Tante Lila memeluknya lebih erat.
“Saya menduga jantungnya kumat akibat bekerja terlalu berat, kurang istirahat dan terlalu banyak merokok. Tapi untuk lebih pasti harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tawar Dokter.
“Nggak usah, Dok. Kami ikhlas, kami mau bawa Ayah pulang biar bisa dikuburkan hari ini juga,” jawab Rangga pahit.
Dokter muda itu tersenyum penuh simpati. Rangga memeluk Bundanya dan menangis bersama. Mungkin saat ini hanya tangis yang mereka butuhkan untuk sedikit demi sedikit menggerus lara. Mungkin rinai air mata akan membantu mereka mengikhlaskan kepergian yang tak disangka-sangka, kehilangan yang tak pernah diduga akan begini caranya.
Jumat, 3 Januari 2014.
Kisahku sudah selesai dibuat. Sudah kutumpahkan ingatan menjelma jadi barisan kalimat, kureka ulang setiap babak kejadian. Aku termangu di depan laptop. Kursor berkedip menanti jemari menekan tombol huruf berikutnya.
Ahh…
Kuteguk sisa cairan di gelas kopi. Jemariku kembali menekan beberapa tombol. Tak ada kata baru yang tertera di layar. Bukan pula menekan tombol simpan, melainkan ‘ctrl + a + delete’. Ini adalah tahun kesepuluh aku melakukan hal seperti ini. Menuangkan kembali ingatan menyakitkan ke dalam sebuah tulisan, menerakan setiap detil kenangan, menyesap kembali rasa sakit yang menghunjam. Sudah sepuluh tahun, gumamku. Sudah sepuluh tahun, tapi kejadian itu terbayang begitu nyata seolah baru kemarin terjadi. Seakan masih bisa kurasa di kulitku hangat tubuh Ayah dalam pelukan saat kami membawanya ke Rumah Sakit. Seakan masih bisa kudengar suaranya baritonnya yang entah bagaimana terasa lembut di telinga. Seakan masih bisa kulihat senyuman lebar miliknya yang membuat hatiku hangat. Ada rasa rindu yang menyeruak.
Bunda juga sudah tiada. Beliau wafat tahun kemarin; kematiannya yang kedua. Aku tak sampai hati mengingat kembali betapa terpukulnya dia. Betapa dia kehilangan keinginan untuk melanjutkan hidup. Sebelah jiwanya tercerabut tanpa peringatan, memukul jiwanya begitu dalam. Kuambil tisu dan menghapus setitik butiran bening di sudut mata. Kurasa tahun depan aku masih akan menulis cerita yang sama. Kumatikan laptop dan lampu. Aku ingin menangis dalam kegelapan.
**
Cerita tentang Bunda ada dalam Melepas Bunda
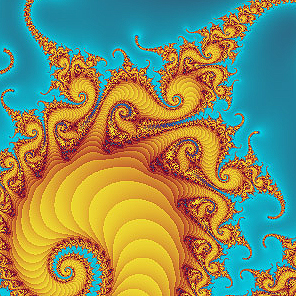
Assalamualaikum, kak. Saya mampir kesini dan terkesan dengan tulisan kakak. Bolehkah saya memakai cerpen ini untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia saya? Saya hanya akan menganalisis unsur intrinsiknya saja, dan akan saya cantumkan nama pengarangnya. Terima kasih, sebelumnya 🙂
Alaikumsalam…
Duh, balasan surel saya ini pasti sudah sangat-sangat terlambat, yah. Terima kasih kamu sudah (tadinya) memilih cerpen ini. Saya sangat menghargai niat kamu.
🙂
Tak pernah ingkar
Kematian kan datang
Tanpa permisi.
Baang, hiks.. 😥
;'(
[…] Cerita tentang hari terakhir ayah ada dalam kisah Titip Rindu Buat Ayah […]
[…] disalahartikan oleh banyak anak. Tulisan tentang seorang ayah yang saya suka salah satunya adalah tulisan Mas Ariga. Akhirnya aku bisa menuliskan soal ayah mas. hehehe. Walau merasa masih agak jauh dari yang […]
[…] Sering saya teringat dirinya kalau mang lagi rindu banget. Seperti saat membaca tulisannya Mas Ariga soal ayah, saat itulah saya merasa rindu dan kehilangan, walau almarhum […]
Jangan nagis dalam kegelapan, kak. Kenapa? Biar gak ada yang tahu, kalau kamu menangis? :’)
http://www.cewealpukat.me/
Iya… :,)
[…] tersebut berupa sebuah cerita pendek berjudul Titip Rindu Buat Ayah. Ya, ini adalah cerita yang saya alami sendiri. Kisah nyata yang pernah menghancurkan hati. […]
Hiks, tentang ayah.. 😦 Kadang saya ‘iri’ dengan mereka yang punya lebih banyak kenangan hingga bisa dituangkan dengan cantik dalam uraian cerita seperti ini. Saya tidak punya banyak kenangan dg ayah saya, waktu itu saya masih 6 tahun. Biasanya kl bikin cerita berdasarkan kenangan yang ingin saya punya dg beliau, jatuhnya jd fiksi. :’)
Pernah juga bikin semacam ini, tapi ttg meninggalnya ibu saya. Tapi ndak kuat nulisnya. Keburu mewek. 😥
Iya, susah nulisnya. Kebawa emosi duluan. ‘behind the story’ cerita ini ada di tulisan ‘tentang ayah tentang rindu’.
Mungkin bisa dengan cara bertanya sama uwak atau orang-orang tua yang masih hidup, Dila. Jadi mereka bisa kasih gambaran tentang orangtua saat masih hidup.
Kalau tulisan tentang Bunda memang aku belum bisa bikin cerpennya. Karena pas Bunda meninggal, aku di kota lain. Untung masih sempat pulang buat menyalatkan.
Dan buat Bunda aku bikin ‘semacam puisi’ judulnya Melepas Bunda. Aku tulis di twitter pada hari yang sama saat beliau meninggal, baru kemudian dipindahkan ke blog. Itu saat-saat yang sangat emosional. *keingat lagi *nyari tisu
Iya, kalau tentang ayah, saya sering tanya kisahnya sama ibu (dulu) dan kakak2 saya. Paling seneng pas bagian kebiasaan2 saya yang tanpa saya sadari ternyata juga kebiasaan beliau. Sekecil apapun itu. Rasanya berharga sekali. 😊
Semoga Ayah dan Ibu Bang Riga diberikan tempat terbaik di sisi Allah dan Bang Riga diberikan ketabahan menerima semua takdir ini.
Orangtua saya juga sudah meninggal, Mama dulu, dan 2 tahun kemudian Papa dan itu semua sudah 16 tahun yang lalu. Tapi, rasa kehilangannya masih kerasa sampai sekarang.
Rindu itu wajar, Bang.. didoakan saja… semoga kita termasuk golongan anak yang dapat menjadi amalan tak terputus untuk orangtuanya… Aamiin… 🙂
Amiin… | Iya, May. Rasanya sampai kapanpun kalau diingat-ingat tetap terasa…. :,)
[…] pelukannya aku merajuk. “Papa, aku kangen. Aku minta […]
[…] Suara sendawa dan tawa kecil yang menyenangkan terdengar berikutnya. Aku ikut tertawa dan menutup telepon. Kuraih ponsel lain dari laci. Ponsel milik Ayah yang baru saja kuhubungi. Airmata kembali menderas. Kehilangan ini entah kapan mampu kurelakan. […]
berkaca2 gue ngebacanya bro…gue baru 120 hari ditinggal pergi bokap…jadi luka hati gue pun masih basah….dan gue menumpahkan semuanya dengan tulisan di blog…smoga kita bisa ketemu & ngobrol2 bro, gue juga suka nulis…thanks for share…
aku ngerti rasanya, Ken.. :’) | Yup, semoga ada waktu dan kesempatan nanti. Thanks udah mampir 🙂
[…] “Ayah, aku rindu.” […]
jangan sekedar rindu di mulut aja mas riga,,,buktikan kalau mas riga rindu sama belio dengan beribadah dan jgn lupa berDOA buat belio,,,
makasih ya mas boer sarannya 🙂
sama2 mas riga…..
duh mas Riga… rindu yang sangat mendalam ya. 10 tahun… berarti tak beda jauh dengan tahun meninggalnya papa saya mas. saya yakin almarhum sudah tenang di sisiNya dan bahagia melihat mas seperti sekarang (eh ini diilhami kisah nyata kan?).
Saya masih belum bisa menuliskan kerinduan ke ayah. 😦
iya, 10 tahun.
mas ryan udah berapa lama ditinggalkan ayahnya?
Th ini 10 th mas
sama-sama meninggal tahun 2004 yah..
Sudah satu dekade, rasanya , masih kayak kemarin.. :’)
Iya mas. Masih ingat almarhum.
sama 🙂
Baru selesai baca. Tanggung jawab, Bang. Airmataku ga berenti2 ini. Aku jadi kebayang Papaku gimana nanti. 😥 Mama juga.
Itu, yg bagian Bapak jatuh dr tempat tidur, mau ngapain atau lagi ngapain sebenernya?
sebenarnya aku nggak tahu juga kenapa ayah bisa terguling dari tempat tidur, waktu itu -dan seterusnya- nggak kepikiranin buat nanya ke bunda. tapi banyak juga yang nanya tentang hal ini, ntar aku tambah keterangan deh. 🙂
semua akan pergi pada waktunya, semoga ketika tiba kita semua telah siap dan rela ya Isti. 🙂
Di bagian pas ayah jatuh berulang x mgkin bisa dibikin lebih detail, pas bunda cerita ke Rangga, ayah jatuhnya kenapa bang..
ditambahi ya? hm hm. sarana yang bagus! 🙂
Di bagian pas ayah jatuh berulang x mgkin bisa dibikin lebih detail, pas bunda cerita ke Rangga, ayah jatuhnya kenapa bang.. 😁😁
True story bg Riga?? Semoga diberi ketabahan ya bg :). Semoga amal ibadahnya diterima. Yg kuat ya…
amiiiin, dika… 🙂
semoga almarhum tenang disisiNYa..dan Mas sekeluarga diberi ketabahan #amin
Sama Mas, aku juga dah berapa tahun ngak pernah bisa menyelesaikan cerita tentang almarhumah Ibuku..:D
amiiin, makasih ya Ronal. 🙂
*semoga tulisan tentang ibu bisa cepat selesai yah.. 🙂
inget bapak bu e d rmh
gak tau dan blm kepikiran klo mereka pergi kya gmn akunya 😦
semua bakal pergi, cuma beda cara. semoga kita semua punya persiapan untuk ditinggalkan/meninggalkan orang-orang yang kita sayang… amiiin. 🙂
mewekkk, apalagi 2 paragraf terakhir *pukpukbangriga. semoga husnul khotimah ya bang, en smoga yang ditinggal bisa selalu kuat *ngeliriknovelkujuga *kitamirip T_T
Amiiin, semoga khusnul khatimah mereka berdua. Makasih, Na. :’)
*ditunggu ya novelnya 🙂
Ikut sedih membaca tulisan ini bang Riga. Smoga beliau berdua mendapat tempat terbaik di sisiNya.
Amiiiin…. Makasih, Lianny.. :’)
turut berduka… 😦
aku juga memiliki begitu banyak duka, sayangnya aku perlu berlatih sangat keras untuk bisa menuangkannya di laptop seperti ini… 😦
terimakasih..
saat menulis ini tepat 10 tahun sejak Ayah pergi, dan aku berulangkali perlu berhenti mengetik untuk menenangkan diri. bahkan ketika telah selesai ditulis, aku masih belum sanggup untuk berbagi, hingga hari ini.
:’)
………
*tepuk tepuk punggung sahabatku…
makasih, Ie… :’)