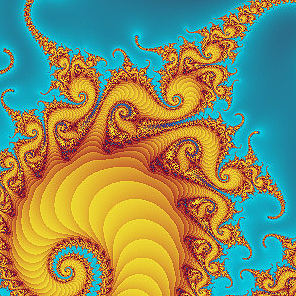A Copy of My Mind mengisahkan perihal Sari dan Alek, dua manusia yang dipertemukan secara kebetulan oleh satu kesamaan : film. Sari menjadikan film sebagai pelepasan atas penatnya hidup di kota besar, sementara Alek mengais rejeki dari pekerjaan sebagai penerjemah teks film (bajakan). Sari, penggemar film bernuansa monster, tak puas dengan hasil penerjemahan teks melancarkan protes pada pemilik lapak DVD bajakan tempat ia sering membeli, tepat pada saat Alek ada di tempat yang sama. Keduanya merasakan ada rasa ketertarikan satu sama lain. Dan dimulailah kisah keduanya.
Saya menemukan kalimat ‘a film by Joko Anwar’ di sampul novel adaptasi oleh Dewi Kharisma Michellia saat pertama kali memegang novel yang saya dapat secara gratis dari Goodreads. (yeayy, thanks Michellia!). Oh, jadi ini novel yang disadur dari sebuah film, begitu yang terbenak di saya. Film apa itu? Saya belum pernah tahu. Dan saya memutuskan untuk tidak mencari tahu hingga saya selesai membaca novel ini secara keseluruhan. Saya membebaskan diri dari ekspektasi, dari keharusan membandingkan antara karya sebelumnya dengan novel ini.
Novel setebal 197 halaman ini berjalan dengan alur lambat. Hingga halaman 134, nyaris tak ada konflik berarti. Cerita berputar di sekitar kehidupan Sari dan Alek, proses pengenalan diri, pekerjaan masing-masing, hingga tumbuhnya cinta. Selipan cerita dari film ada di sana-sini. Beberapa bagian bahkan menyentil kejadian nyata. Seru! Gaya bahasa yang dipakai Michella untuk kedua tokohnya lugas, mengalir lancar. Bercerita dengan teknik dua POV, setiap tokoh menawarkan rasa yang berbeda. Cara pikir Sari dan Alek dijabarkan dengan runtut diselingi humor satir perihal kehidupan. Menyegarkan… walau akhirnya membosankan. Apa enaknya membaca novel tanpa konflik?
Mulai halaman 135, barulah konflik ‘sebenarnya’ diperkenalkan. Karena tindakan impulsif Sari mencuri DVD milik Ibu Mirna, salah satu klien yang sedang mendekam di ‘penjara bintang lima’, Sari dan Alek menemui masalah. Ketika sampai di halaman ini, saya sedikit khawatir. Bukan apa-apa, konflik baru dimulai sedangkan sisa halaman novel terlihat semakin tipis. Apakah konflik dapat di atasi dengan baik? Seperti apa penyelesaiannya? Akhirnya saya terpaksa kecewa karena cerita berakhir ‘begitu saja’. Saya cuma bisa berujar, ‘Oh’.
Di bagian ‘ucapan terima kasih’, Michellia menyebutkan bahwa sutradara film A Copy of My Mind, Joko Anwar, membebaskan ia untuk ‘menuliskan novel adaptasi sebebas-bebasnya, tanpa pembatasan’. Ia juga dibolehkan untuk menuliskan adegan tambahan, bahkan mengoreksi adegan dalam film. Sebuah privelese bagi penulis yang sebelumnya menelurkan karya perdana ‘Surat Panjang Tentang Jarak Kita yang Jutaan Tahun Cahaya’. Kemewahan ini membuat saya bertanya-tanya : sudahkah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Saya belum menonton film aslinya yang berhasil diputar pertama kali pada seksi Film Kontemporer Dunia pada ajang Festival Film Internasional Toronto 2015 yang bergengsi. Apakah ujung kisah film sama dengan versi novel? Saya tak tahu. Seandainya akhir cerita film memang ‘seperti itu’, tidakkah penulis berpikiran untuk memberikan sebuah penyelesaian yang lebih ‘dramatis’ ketimbang akhir yang menggantung? Bukankah empunya film sudah memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya? 🙂
<a href=”https://www.goodreads.com/review/list/37294608-attar-arya”>